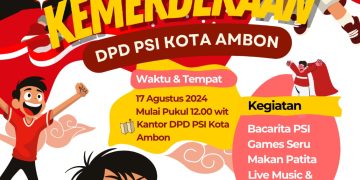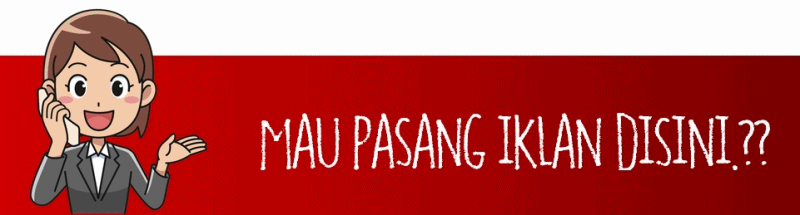BacaritaMaluku. com–Ambon, Maluku; Banyak yang menganggap bahwa Nietzsche menolak keberadaan Tuhan secara mutlak. Padahal pernyataan ini memiliki makna tidak sesempit itu: ia merupakan kritik epistemik terhadap masyarakat modern yang gampang mencederai nilai-nilai absolut keagamaan.
Nietzsche tidak menyatakan kematian Tuhan secara teologis, melainkan sebagai akhir dari otoritas moral yang tidak lagi menjadi pijakan ontologis bagi manusia modern. Dalam konteks ini pernyataan tersebut mesti di lihat sebagai kritik epistimologis dalam baik itu konteks historis maupun heremeneutik yang lebih luas agar tidak terjebak dalam interpretasi berdasarkan teks semata.
Saya memulai tulisan ini dengan kutipan tersebut di atas bukan untuk menegaskan nihilsime, tetapi sebagai cara untuk memahami bagaimana wacana “kebenaran” yang terus mengalami perdebatan. Termasuk sebagaimana yang terjadi dengan pernyataan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, tentang sopi dan legitimasi agama. Dalam sudut pandang yang sama, pernyataan tersebut dapat di baca sebagai bentuk kritik epistemik atas relasi antara norma religius, hukum negara, adat dan realitas sosial.
Olehnya itu untuk memulai tafsiran ini, saya akan mengutip secara verbatim pernyataan Vanath, yang tak sedikit mengandung polemik bagi masyarakat maluku yang sempat viral.
“Tapi yang bapak dong khotbah-khotbah selama ini orang minum sopi tambah banya atau tamba sedikit? Tambah banya toh? Itu artinya hukum Tuhan itu dia seng mempan. Karena hadits ya, termasuk firman-firman di Alkitab itu akang su seng manjur lai untuk menyadarkan orang tentang barang itu. Ya, polisi mau gunakan hukum negara ada keterbatasan-keterbatasan, caranya adalah menggunkan hukum ekonomi”
Pernyataan tersebut terjadi saat Abdullah Vanath memberikan sambutan pada Senin malam, 21 Juli 2025 saat menghadiri acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Secara kontekstual, pernyataan itu mucul karena ada tuntuntan untuk melegalisasi sopi dalam Regulasi Daerah sebagai minuman khas Maluku. Dari sisi hukum positif, tuntutan tersebut tentunya melewatis batas etis masyarakat di mana minuman memabukan—terutama sopi—yang secara historis di lihat sebagai biang kericuhan yang sering terjadi.
Jika kita melihat pada akar permasalahannya, tuntutan ini bukan datang dari pengguna yang sering mengkonsumsi minuman keras, tetapi dari produsen yang menggantungkan hidupnya pada produksi sopi sebagai bagian dari ekonomi tradisional. Para produsen ini adalah petani nira, penyuling, hingga keluarga-keluarga kecil yang hidup di pinggiran sistem ekonomi formal. Fakta hari ini, prodesen sopi telah menjadi jalur bertahan hidup dalam lanskap ekonomi yang tidak menyediakan cukup ruang bagi kerja yang layak dan akses produksi.
Olehnya itu, dengan segala problematika yang ada, saya melihat pernyataan “hukum Tuhan sudah tidak berlaku” dari Abdullah Vanath ini menarik untuk di kaji baik secara filosofis, ekonomi dan kritik keagamaan. Olehnya itu saya mengerecut pembahasan ini pada tiga aspek, yakni yang pertama sebagai kritik epistemologis, kedua sebagai kertik ekonomi dan ketiga kritik agama.
Sebagai kritik epistemologis, pernyataan tersebut mengandung kebenaran jika kita meletakkan sopi sebagai minuman yang memabukkan, bukan sebagai minuman berbasis genealogis dan kearifan lokal. Selain sebagai kritik epistemik, pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan afirmatif atas penyalagunaan sopi bukan sebagai minuman yang memiliki nilai yang berhubungan dengan adat.
Sebagai kerangka epistemologis, ungkapan bahwa “hukum Tuhan sudah tidak berlaku” mencerminkan tumbangnya runtuhnya fondasi metafisik moralitas dan keimanan masyarakat. Pernyataan ini mesti dilihat bukan dalam kerangka penolakan nilai-nilai Ilahiah, justru ini adalah refleksi kritis terhadap bagaimana masyarakat kita mengalami desakralisasi dalam memaknai moral dan dosa.
Dalam konteks ini, ungkapan Nietzsche “Tuhan telah mati” menemukan relevansinya. Nietzsche tidak sedang mengumumkan kematian entitas Ilahi secara literal, tetapi mengkritik bagaimana modernitas telah membunuh kebutuhan manusia terhadap Tuhan sebagai fondasi, nilai dan makna hidup. Maka ketika di katakan bahwa “hukum Tuhan sudah tidak berlaku lagi” hal itu mencerminkan keadaan nihilistik yang sama seperti di katakan Nietzsche— sebuah dunia yang kehilangan pusat nilai absolutnya, dan bergulat dengan kekosongan moral dan etik. Sederhananya, ketika kita mengkonsusmsi sopi lalu mabuk, maka di situlah letak Hukum Tuhan sudah tidak berlaku bagi kita.
Kedua, sebagai Kritik Ekonomi. Tutuntan legalisasi sopi bukanlah datang dari jeritan para pengguna atau pemabuk, melainkan suara ekonomi lokal yang meronta mencari legitimasi hukum. Sopi bukanlah cairan alkohol; ia adalah simbol ikatan adat sebagian orang Maluku, simbol pertemuan tradisi, kearifan lokal. Ketika Negara menolak mengakuinya secara hukum, yang tercederai bukan saja norma tetapi nasib ribuan produsen yang menggantungkan hidup dari penyulingan tradisonal ini.
Maka hukum Ekonomi yang di maksud Vanath, harus di interpretasi sebagai solusi dan ikhtiar agar sumber daya lokal tersebut tidak terbuang tanpa nilai, baik dari sisi kearifan maupun ekonomis. Lebih jauh, hukum ekonomi ini bukan sekedar kalkulasi untug rugi pasar, tetapi harus menjadi prinsip etis yang memapu menjaga nilai adat dan kebutuhan modern.
Dalam konteks sopi, legalisasi bukan dilihat sebagai transforamsi moral. Tujuannya bukan sekedar agar sopi dapat di jual bebas, melainkan agar produsen—yang selama ini beroperasi dalam ruang dan bayang ilegal—dapat mendapatkan hak ekonomi yang setara. Olehnya itu,
solusi yang saya maksud adalah bagaimana pemerintah dapat melakukan penelitian lanjutan dan inovasi dalam bentuk ekstraksi dan diversifikasi dari sopi.
Sebagai hasil destilasi etanol tradisional, sopi memiliki potensi untuk di kembangkan menjadi bahan bakar alternativ seperti bioetanol, gas rumah tangga ramah lingkungan, disinfektan hingga bahan-bahan industri lainnya.
Dengan cara ini, produksi besar-besaran sopi tidak lagi mencemaskan aspek moral masyarakat, karena hasil akhirnya bukan untuk memambukkan tetapi sebagai solusi untuk menyokong keberlanjutan dan kemandirian energi lokal dan kearifan lokal. Hal ini juga merupakan alternativ untuk menjaga kedaulatan daerah di tengah ketidakpastian dan ancaman global yang semakin menunjukan gejala krisis global, baik dalam bentuk pangan maupun energi.
Yang ketiga kritik Agama. Pernyataan Abdullah Vanath, yang menyatakan bahwa hukum agama sudah tidak berlaku lagi dalam konteks pengendalian konsumsi sopi, memang memantik kegelisahan dan kritik dari berbagai pihak—mulai dari MUI Provinsi Maluku, aliansi mahasiswa, hingga tokoh-tokoh keagamaan. Namun, respons yang muncul kebanyakan berhenti pada reaksi skriptural semata, seolah ucapan tersebut adalah penghinaan terhadap doktrin agama.
Padahal jika ditilik lebih dalam, Vanath sebenarnya sedang mengangkat cermin untuk menunjukkan kebuntuan epistemologis dalam pendekatan dakwah dan khotbah keagamaan yang selama ini lebih bersifat tematik, bukan transformatif. Ia menyoroti fakta bahwa meskipun para pendeta dan ustadz terus-menerus menyerukan larangan, realitas sosial tidak berubah—sopi tetap dikonsumsi, mabuk tetap berlangsung.
Dalam titik ini, kritiknya bukan diarahkan pada Tuhan atau agama itu sendiri, melainkan pada metode representasi dan penyampaian nilai-nilai agama yang tak lagi efektif dalam menembus kesadaran masyarakat.
Alih-alih tersinggung, kritik ini justru harus dibaca sebagai ajakan untuk introspeksi kolektif bagi para tokoh agama agar merumuskan ulang cara mereka memahami dan merespons realitas. Bahwa hukum agama tidak lagi berfungsi bukan karena hilangnya iman, tapi karena jarak metodologis yang semakin menganga antara teks suci dan struktur kehidupan sehari- hari umat.
Oleh karena itu, menggantikan pendekatan hukum agama dengan hukum ekonomi dalam konteks sopi bukan berarti mengganti Tuhan dengan pasar, melainkan menandai perlunya pendekatan kontekstual yang lebih menyentuh akar persoalan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Di sinilah agama ditantang bukan untuk mengutuk, tetapi untuk bertransformasi menjadi kekuatan etis yang hadir secara substantif dalam kehidupan umatnya.
***
Pernyataan Wakil Gubernur Maluku yang menyatakan bahwa hukum agama tidak berlaku lagi dan harus digantikan oleh hukum ekonomi, membuka ruang problematik yang sangat serius, bukan hanya secara moral, tetapi juga secara epistemologis dan politik pengetahuan.
Dalam terang pemikiran Nietzsche, pernyataan ini dapat dibaca sebagai gejala dari matinya sistem nilai lama, namun yang menjadi soal bukan sekadar soal kematian nilai lama, melainkan kegagalan dalam melahirkan nilai baru yang bermakna bagi kehidupan bersama.
Sepanjang tulisan ini telah ditegaskan bahwa sopi, dalam konstruksi masyarakat Maluku, bukan hanya persoalan alkohol atau barang dagangan, tetapi menyangkut dimensi simbolik, spiritual, dan relasional yang sudah terikat kuat dalam tubuh sebagain masyarakat. Mengatur sopi lewat hukum ekonomi, tanpa membaca kedalaman makna yang dimilikinya dalam ruang kultural, adalah bentuk kekerasan epistemik—sebuah pemaksaan cara berpikir modern yang mengabaikan kosmologi lokal.
Kritik terhadap pernyataan tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap perubahan, melainkan seruan agar segala bentuk perubahan dilakukan dengan kesadaran akan konteks ekonomi dan struktur nilai yang telah terbentuk di masyarakat. Agama, dalam hal ini, tidak semata dipahami secara skriptural, melainkan sebagai horizon etis dan simbolik yang mengikat masyarakat dalam solidaritas dan tanggung jawab moral.
Oleh karena itu, tulisan ini mesti di lihat sebagai upaya menegaskan bahwa setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut aspek budaya, spiritualitas, dan kehidupan sehari-hari masyarakat, tidak boleh dilepaskan dari pertimbangan epistemik dan etis yang menyeluruh.
Kebenaran bukan sekadar hasil hitung-hitungan untung-rugi, melainkan juga sesuatu yang dibangun secara historis, simbolik, dan kolektif. Dalam konteks ini, sopi dan seluruh perbincangannya bukanlah tentang legal atau ilegal, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan nilai, sejarah, ekonomi dan kehidupan itu sendiri.
Namun yang harus menggarisbawahi bahwa dalam konteks masyarakat yang plural secara budaya, spiritualitas, dan tingkat literasi, setiap pejabat publik, termasuk Abdullah Vanath sebagai Wakil Gubernur Maluku, dituntut untuk cermat dan bijak dalam memilih bahasa. Pernyataan yang mengandung muatan paradoksal, satiris, atau provokatif memang dapat membuka ruang diskusi yang luas, namun pada saat yang sama juga berisiko besar disalahpahami oleh sebagian besar masyarakat yang tidak terbiasa dengan gaya komunikasi semacam itu.
Dalam ruang publik yang sarat interpretasi, kata-kata tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk realitas sosial. Oleh karena itu, secerdas-cerdasnya seorang pemimpin dalam berpikir, ia harus lebih cerdas lagi dalam mengolah bahasa—agar tidak jatuh ke dalam jebakan kesalahpahaman yang justru mengaburkan niat baik di balik pernyataan tersebut. Apalagi di tengah masyarakat yang ragam pemahamannya luas, di mana tidak semua terbiasa membaca dunia lewat kritik sastra atau filsafat bahasa. Maka, kehati-hatian dalam berbahasa bukan sekadar etika komunikasi, tetapi bagian penting dari tanggung jawab publik seorang pemimpin.***